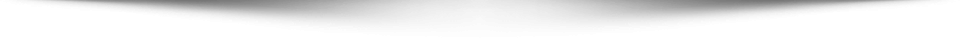Cakrawala Arunika membentang di atas kota terapung Taman Wulan, sebuah kota yang tampak damai dan maju dengan teknologi serta ketentraman. Namun, Dewi tahu, di balik kemilau itu tersimpan bayangan yang tak tampak. Ia datang ke kota ini sebagai peneliti psikologi, membawa luka lama yang belum pulih.
Di pusat kesehatan mental Taman Wulan, Dewi bertemu dengan Arman—pria misterius dengan tatapan tenang dan kata-kata yang menusuk lembut ke jiwa. Arman bukan psikolog resmi, hanya seorang relawan yang selalu hadir saat orang-orang rapuh membutuhkan teman bicara. Tapi, ada yang mengganggu Dewi: pasien-pasien Arman yang dulu ceria, perlahan menghilang tanpa jejak.
Suatu hari, Dewi mulai menyelidiki. Ia menemukan pola gelap: sesi panjang dengan Arman, hilangnya pasien dari catatan resmi, dan pesan misterius yang muncul saat ia menggali arsip rahasia. Semua tanda menunjuk pada Arman—yang ternyata lebih dari sekadar pendengar.
Konfrontasi tak terelakkan. Arman mengungkapkan bahwa ia menggunakan empati bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengendalikan dan membebaskan dari “kegaduhan batin”—dengan cara yang berbahaya. Dewi dihadapkan pada pilihan sulit: mengungkap kebenaran yang bisa merusak ketenangan Taman Wulan, atau membiarkan kegelapan itu terus bersemayam dalam bayang-bayang kota.
Tiga minggu berlalu, dan Taman Wulan tetap sunyi. Arman hilang tanpa jejak, dan laporan Dewi tak mendapat tanggapan. Kota itu lebih memilih kenyamanan daripada kebenaran.
Baca Juga Terbaru
—
Dewi pertama kali berbicara dengan Arman di taman meditatif di Distrik Senja, sebuah sudut kota Taman Wulan yang selalu diselimuti kabut tipis di pagi hari. Saat itu, ia sedang mencatat gelombang emosi kolektif menggunakan alat pemindai aura, ketika suara lembut tiba-tiba memecah kesunyian.
“Orang sering pikir tempat ini menenangkan,” kata Arman dari belakang. “Padahal, kalau kau diam cukup lama, kau bisa dengar bisikan dari luka yang tak terlihat.”
Dewi menoleh. “Aku Dewi,” ucapnya.
“Arman. Aku di sini sebagai teman yang mendengar, bukan psikolog.”
Hari-hari berlalu, dan Dewi mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Pasien-pasien yang datang menemui Arman tampak pulih secara tiba-tiba, lalu menghilang. Senyum mereka berubah menjadi kosong, dan mata mereka kehilangan kilau.
Sari, wanita tua yang biasa duduk di taman, menghilang. Arman berkata, “Sari sudah damai.” Tapi Dewi tahu, itu bukan jawaban.
Baca Juga Berita Populer
Suatu malam, Dewi menerima pesan misterius di layar pribadinya:
“Jangan gali terlalu dalam, Dewi.”
—
Dewi menyelinap ke pusat arsip Kota Induk. Ia temukan nama Arman berulang di catatan terakhir pasien-pasien yang hilang. Saat bersiap keluar, layar menyala:
“Kau mencari apa yang tak ingin ditemukan.”
Sesampainya di rumah, Arman sudah menunggu. Duduk tenang, senyum damai, mengenakan batik kelam.
“Aku tahu kau penasaran,” katanya. “Karena kau juga terluka. Seperti mereka. Seperti aku.”
Dewi sadar: Arman bukan sekadar memahami luka—ia hidup di dalam luka itu. Ia masuk ke ruang terdalam setiap jiwa, lalu mematikan bagian yang paling kacau… dan kadang, seluruhnya.
—
“Kenapa kau lakukan ini?” tanya Dewi.
“Aku bantu mereka diam,” jawab Arman. “Itu bukan kematian. Itu kebebasan.”
“Tidak. Itu pembunuhan.”
Arman tersenyum. “Silakan laporkan aku. Tapi kau tahu, Taman Wulan tidak dibangun di atas kebenaran. Tapi di atas ketenangan.”
Saat ia melangkah pergi, suaranya terdengar lagi:
“Kalau suatu hari kau lelah berperang dengan dirimu sendiri, kau tahu di mana mencariku.”
—
Tiga minggu kemudian, kota tetap tenang. Laporan Dewi dibalas dengan satu baris singkat:
“Terima kasih atas partisipasi Anda dalam menjaga harmoni kota.“
Di pangkuan Dewi, buku catatannya terbuka. Di halaman terakhir:
“Empati tanpa hati nurani hanyalah pisau yang dibungkus senyuman.”
Di bawah lampu taman, seseorang berdiri. Bukan Arman, tapi… bayangannya. Diam. Menatap.
Dan Dewi tahu: bayangan itu belum pergi.
Mungkin tidak akan pernah.
—
TAMAT
Disclaimer:
Cerita ini sepenuhnya fiksi. Semua tokoh, tempat, dan kejadian adalah rekaan semata.